PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENERAPAN UUPA 1960 DI KALIMANTANTENGAH MENYONGSONG ERA OMNIBUS LAW
Klik Untuk Lebih Jelas : PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENERAPAN UUPA 1960 DI KALIMANTANTENGAH MENYONGSONG ERA OMNIBUS LAW
Klik Untuk Lebih Jelas : PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENERAPAN UUPA 1960 DI KALIMANTANTENGAH MENYONGSONG ERA OMNIBUS LAW
Klik Untuk Lebih Jelas : PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENERAPAN UUPA 1960 DI KALIMANTANTENGAH MENYONGSONG ERA OMNIBUS LAW
Klik Untuk Lebih Jelas : PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENERAPAN UUPA 1960 DI KALIMANTANTENGAH MENYONGSONG ERA OMNIBUS LAW
Palangka Raya, 4 Juni 2020 – PALANGKARAYA, KOMPAS – Tumpang tindihnya peraturan dan undang-undang terkait hukum adat memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pemegang izin. Kemudian munculah RUU Cipta Kerja yang dikenal dengan omnimbus law yang dinilai memperkeruh suasana dan berpotensi menambah konflik.
Hal itu terungkap dalam serial webinar dengan tema “Peranan Hukum Adat dalam Penerapan UUPA 1960 di Kalteng Menyongsong Era Omnimbus Law” yang diselenggarakan oleh Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Kalimantan bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, di Palangkaraya, Kamis (4/6/2020). Webinar itu merupakan diskusi kedua yang diselenggarakan dua lembaga tersebut.
Hadir sebagai pemateri dalam webinar, yakni Antropolog Dayak Marko Mahin dari Lembaga Studi Dayak 21, Ketua Manajemen Pengetahuan YLBHI Rakhma Mary, dan Prof. Kurnia Warman sebagai pakar hukum agrarian dari Universitas Andalas. Hadir juga sebagai pemantik diskusi Yando Zakaria pengamat Masyarakat Hukum Adat.
Menurut Marko Mahin, sejak awal kehidupan Suku Dayak sudah mengatur ruang kelola hutan, tanah, hingga kebutuhan hidupanya melalui hukum adat. Hukum adat itu dibuat berdasarkan kepercayaan termasuk hal-hal bersifat mistis dan religius.
“Orang-orang lupa jika masyarakat adat juga berkembang seiring dengan waktu apalagi ketika begitu banyak aturan itu masuk dan memengaruhi kehidupannya. Di satu sisi, omnimbus law juga tidak berpihak pada masyarakat adat,” kata Marko.
Hal serupa juga diungkapkan Kurnia Warman. Menurutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) memposisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam hukum agraria (hukum positif tidak tertulis). Jadi UUPA tidak menghapus keberadaan hukum adat sebagai hukum yang berlaku atas tanah di Indonesia.
“Tak hanya diakui hukum agraria, pengakuan hak masyarakat adat itu juga diatur diberbagai aturan sektoral lainnya,” kata Kurnia.
Ia mencontohkan, pada aturan Kehutanan (UU 41/1999), Perkebunan (UU 39/2014), Sumber daya Air, PertambanganMinerba, Ketenagalistrikan (UU 30/2009), UU Migas, UU Panas Bumi, dan banyak aturan lagi.
“Dalam aturan sectoral itu menyatakan, pemegang izin usaha wajib mengurus perolehan tanahnya menurut Hukum Agraria. Artinya dalam perolehan tanah utk izin usaha SDA wajib mengakui hak masyarakat berdasarkan hukum adat,” ungkap Warman.
Namun, hal itu kerap menjadi bulan-bulanan pemerintah dalam pemberian ijin. Pengusaha atau pemegang izin pun kerap mengeliminasi hak adat dengan berbagai alasan.
Seperti yang terjadi di Desa Penyang, Kabupaten Kotawaringin Timur di mana tiga warganya ditangkap karena dituduh mencuri. Padahal mereka memanen di lahan milik masyarakat atau berada di luar HGU.
Dalam hak asal-usul di UUPA 1960, apabila ada benda di atas tanah, dan benda itu tidak diketahui asal-usulnya oleh pemilik tanah, benda itu memberikan manfaat bagi pemilik tanah, maka benda itu menjadi milik pemilik tanah karena ada azas asesi di situ, perlekatan.
Namun apa daya tiga orang itu ditangkap dan dipenjara. Mereka sudah menjalani 10 kali persidangan, padahal perusahaan yang mereka lawan PT HMBP menanam di atas tanah yang jelas berada di luar Hak Guna Usaha.
Dalam diskusi juga diungkap masalah di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalteng di mana masyarakat adat Laman Kinipan harus menyaksikan keberingasan perusahaan yang menggerus hutan kelola adat yang sudah mereka kelola ratusan tahun.
Rakhma Mary mempertegas dengan adanya RUU Cipta Kerja akan menambah runyam konflik agrarian di Indonesia. Bukan hanya kriminalisasi tetapi juga perampasan tanah akan masih terjadi karena RUU itu melanggar prinsip dan filosofi UUPA 1060 atau hukum agrarian lainnya.
“Argumentasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk terpatahkan dengan mencermati seluruh pasal di Omnimbus Law, ini merupakan ajang perampokan besar-besaran sumber daya alam/agrarian,” kata Rakhma.
Rakhma menjelaskan, dari data YLBHI mencatat dalam dua bulan saja di tahun 2020 sudah ada 16 kasus perampasan tanah yang terjadi di Indonesia. Lalu setidaknya terdapat 70 keluarga kehilangan lahan, lebih dari 900 keluarga terancam kehilangan lahan dan lebih dari 40 keluarga merupakan masyarakat adat yaitu 30 SAD di Jambi dan sembilan keluarga masyarakat adat Minahasa di Kelelendoy, Sulawesi Utara.
“Parahnya lagi aparat menjadi backing para pemilik modal ini sehingga penegakan hukum tidak jalan dan kriminalisasi di mana mana. Ironinya, omnimbus law tidak bisa jadi solusi dan praktek seperti ini akan lebih parah lagi,” kata Rakhma.
Yando Zakaria mengingatkan jika pengakuan masyarakat adat harus kembali ke dalam diri masing-masing. Tidak perlu lagi berdebat panjang soal masyarakat hukum adat, tetapi isinya yang lebih penting dan harus dibahas di nasional maupun di daerah.
“Kalau mau bikinan lapangan kerja gak perlu omnimbus law, bikin perppu mencabut pasal 67 ayat 2 UU kehutanan itu ada 40 juta pekerja yang dibutuhkan di sana. Sekarang ini saatnya mengisi diskurs masyarakat adat tetapi kenalilah apa sebenarnya itu, sehingga keluar dari perdebatan yang kontra produktif,” tutup Yando.
***Selesai***

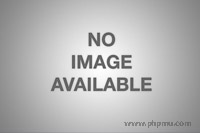 Terdampak Banjir, Ucu Anyik Rindu Berladang
Terdampak Banjir, Ucu Anyik Rindu Berladang