KARBON, TANAH DAN MARTABAT HIDUP
Klik Untuk Lebih Jelas : KARBON, TANAH DAN MARTABAT HIDUP
Klik Untuk Lebih Jelas : KARBON, TANAH DAN MARTABAT HIDUP
Klik Untuk Lebih Jelas : KARBON, TANAH DAN MARTABAT HIDUP
Klik Untuk Lebih Jelas : KARBON, TANAH DAN MARTABAT HIDUP
Di Kalimantan, krisis iklim tidak pernah hadir sebagai angka atau grafik. Ia hadir sebagai sungai yang meluap tak terduga, kemarau yang memanjang, gambut yang mengering, dan ladang yang kian terdesak. Di tanah ini, hutan, gambut, dan ladang bukan sekadar bentang alam, melainkan ruang hidup yang membentuk identitas, pangan, dan martabat masyarakat adat. Karena itu, ketika proyek-proyek karbon masuk dengan bahasa global tentang mitigasi iklim dan penyelamatan bumi, pertanyaan yang paling mendasar bukanlah berapa banyak karbon yang dapat diserap, melainkan bagaimana kehidupan manusia di atas tanah ini dihormati dan dijaga.
Pasar karbon menawarkan janji yang terdengar mulia: emisi yang dihasilkan di satu tempat dapat diimbangi dengan penyerapan karbon di tempat lain. Kalimantan, dengan hutan dan gambutnya, lalu diposisikan sebagai penyangga iklim dunia. Namun cara pandang ini kerap mereduksi tanah menjadi sekadar ruang teknis, dan masyarakat adat menjadi variabel tambahan dalam perhitungan proyek. Risiko terbesar dari pendekatan semacam ini adalah terulangnya pola lama penguasaan lahan, kini dibungkus dalam bahasa hijau dan kontrak yang rapi. Tanah memang tidak dirampas secara kasar, tetapi perlahan dikunci melalui larangan, pembatasan, dan kewajiban yang memisahkan masyarakat dari cara hidupnya sendiri.
Bagi masyarakat Dayak, tanah bukanlah properti yang bisa dipisahkan dari kehidupan. Tanah adalah ibu yang memberi makan, air, dan makna. Ladang berpindah, kebun campur, hutan adat, dan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan lokal bukan praktik kuno yang harus ditinggalkan, melainkan sistem agroekologi yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Api kecil yang dijinakkan, air gambut yang dijaga tetap tinggi, dan siklus ladang yang memberi waktu tanah untuk beristirahat adalah bagian dari etika hidup yang telah lama melindungi hutan dan gambut dari kerusakan besar.
Namun dalam banyak skema karbon, praktik-praktik ini justru dipandang sebagai ancaman. Ladang dipertanyakan, pembakaran terkendali dilarang tanpa dialog, dan pangan lokal terpinggirkan demi stabilitas angka emisi. Secara ekologis, mungkin ada keberhasilan jangka pendek. Tetapi secara sosial, muncul kecemasan baru: ketergantungan pada insentif karbon, melemahnya kedaulatan pangan, dan terpinggirkannya pengetahuan adat yang tidak tercatat dalam laporan teknis. Keberhasilan iklim versi proyek tidak selalu berarti keberlanjutan hidup versi komunitas.
Dalam terang iman Kristiani, krisis ekologis tidak pernah berdiri sendiri. Ensiklik Laudato Si’mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan selalu terkait dengan ketidakadilan sosial. Bumi diperlakukan sebagai objek eksploitasi ketika manusia dan relasinya dengan alam direduksi menjadi persoalan teknis semata. Pertobatan ekologis yang sejati menuntut perubahan cara pandang, yakni dari menguasai menjadi merawat, dari menghitung menjadi mendengarkan. Upaya penyelamatan iklim yang mengorbankan kaum kecil dan masyarakat adat bertentangan dengan semangat keutuhan ciptaan yang menjadi panggilan iman.
Pesan ini menemukan gaung yang kuat dalam kosmologi Dayak. Dalam pandangan hidup masyarakat Dayak, manusia bukan penguasa mutlak alam, melainkan penjaga relasi antara tanah, air, hutan, dan kehidupan yang tak kasat mata. Ketika relasi ini dilanggar, ketika tanah hanya dilihat sebagai komoditas atau gudang karbon, maka kerusakan bukan hanya ekologis, tetapi juga spiritual. Bumi rusak bukan karena manusia hadir, melainkan karena manusia kehilangan hormat pada batas-batasnya.
Di titik inilah JPIC Kalimantan menegaskan sikapnya. Proyek karbon tidak boleh dipahami semata sebagai mekanisme pasar atau instrumen teknokratis. Ia harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, martabat manusia, dan keutuhan ciptaan. Hak atas tanah dan wilayah adat harus menjadi fondasi, bukan catatan kaki. Pangan lokal tidak boleh dikorbankan atas nama mitigasi iklim. Pengetahuan adat harus diakui setara dengan pengetahuan ilmiah, karena justru pengetahuan inilah yang selama generasi menjaga hutan dan gambut tetap hidup.
Kalimantan tidak menolak tanggung jawab global terhadap krisis iklim. Namun kontribusi itu tidak boleh dibangun di atas pengorbanan cara hidup masyarakat lokal. Karbon yang bermartabat adalah karbon yang tinggal bersama ladang, kebun, hutan, dan komunitas yang berdaulat. Gambut yang basah, pangan yang hidup, dan manusia yang memiliki ruang untuk menentukan masa depannya sendiri bukan hambatan bagi penyelamatan bumi, melainkan tanda bahwa bumi masih diperlakukan sebagai rumah bersama, bukan sebagai objek transaksi.
Pada akhirnya, menyelamatkan iklim berarti memulihkan relasi. Relasi antara manusia dan tanah, antara iman dan keadilan, antara masa depan bumi dan kehidupan hari ini. Selama tanah Kalimantan masih diingat sebagai ibu, bukan sekadar aset karbon, masih ada harapan bahwa upaya menjaga bumi tidak akan berubah menjadi bentuk baru ketidakadilan. Karena tanah, seperti iman yang hidup, selalu menuntut kesetiaan, bukan hanya janji. (Esel)

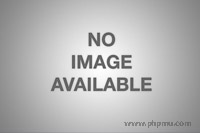 KARBON, TANAH DAN MARTABAT HIDUP
KARBON, TANAH DAN MARTABAT HIDUP